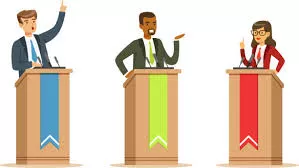Latar Belakang Hari Konservasi Alam Sedunia
Hari Konservasi Alam Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 28 Juli, merupakan ajakan bagi seluruh dunia untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian alam sebagai sumber kehidupan utama bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Peringatan ini bermula dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup Manusia yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972.
Mengutip dari Greenpeace.org, pada konferensi tersebut, masalah kerusakan alam mulai dibahas secara global, menyadari pentingnya aksi kolektif dalam menjaga kelestarian bumi. Sejak saat itu, Hari Konservasi Alam Sedunia menjadi simbol penting dalam mendorong tindakan nyata untuk melindungi ekosistem.
Konservasi Sejak Abad ke-19
Kesadaran tentang perlunya konservasi sudah tumbuh jauh sebelum peringatan ini ditetapkan pada tahun 1972. Pada abad ke-19, tokoh-tokoh seperti John Evelyn dan John Muir mulai menyerukan perlindungan terhadap ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati, yang menjadi dasar gerakan konservasi modern.
Baca juga: Hari Konservasi Alam Sedunia 28 Juli: Tujuan dan Cara Merayakan
Eksploitasi Alam Indonesia Sejak Masa Kolonial
Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, telah mengalami banyak ekses eksploitasi alam, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Salah satu contoh eksploitasi alam yang besar terjadi pada masa pemerintahan VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) di Batavia (sekarang Jakarta). Penebangan hutan dilakukan secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, pangan, dan bangunan. Hutan lebat di kawasan Ommelanden, yang berada di luar tembok kota Batavia, menjadi sasaran utama.
Dampak Eksploitasi Hutan di Batavia
Penebangan hutan yang tidak terkendali berdampak langsung terhadap lingkungan. Pada 1683, laporan dari lembaga pengelola kawasan Ommelanden menyebutkan bahwa Sungai Ciliwung tidak lagi bisa dilayari akibat aliran air yang terganggu oleh tumpukan kayu. Masalah tersebut berlanjut dengan terjadinya banjir tahunan di Batavia, yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.
Pemerintah kolonial akhirnya mengeluarkan larangan penebangan pohon pada 1696, namun pengawasan yang lemah membuat pembalakan liar terus terjadi. VOC menghadapi kesulitan mengatasi kerusakan hutan karena keterbatasan sumber daya manusia dan logistik.
Sistem Tanam Paksa dan Deforestasi
Pada 1830, sistem tanam paksa diperkenalkan, yang menyebabkan pembukaan lahan secara besar-besaran untuk pertanian. Ini memperburuk kondisi hutan dan memicu deforestasi di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa. Para ilmuwan mulai mengingatkan akan dampak kerusakan hutan terhadap keseimbangan lingkungan dan perubahan iklim.
Respons Pemerintah Kolonial
Pada 1846, Direktur Perkebunan Hindia Belanda menulis surat kepada Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen, mengangkat persoalan kerusakan hutan di Jawa. Sebagai respons, pemerintah kolonial mengundang J. Mollier, seorang ahli kehutanan, untuk mengelola kembali hutan di Pulau Jawa. Ini menghasilkan pembentukan Jawatan Kehutanan dan penerbitan Undang-Undang Kehutanan Jawa-Madura yang mengatur pengelolaan hutan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
Namun, meskipun ada regulasi, kerusakan lingkungan tidak berhenti. Pendudukan Jepang selama Perang Dunia II menyebabkan pembabatan hutan kembali dalam skala besar untuk mendukung kebutuhan pertanian dan bahan bakar.
Eksploitasi Alam pada Masa Pendudukan Jepang
Selama pendudukan Jepang, eksploitasi alam di Indonesia kembali meningkat. Pemerintah Jepang memobilisasi masyarakat untuk membuka hutan demi kepentingan pertanian dan kebutuhan militer. Salah satu proyek besar yang dilakukan adalah pembukaan desa pertanian Yamada di pesisir Jawa yang mencakup 1.500 hektare lahan.
Pencaplokan besar-besaran hutan ini menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan yang berujung pada banjir dan kerusakan ekosistem. Kesejahteraan masyarakat lokal juga terpinggirkan karena hasil eksploitasi lebih banyak digunakan untuk mendukung kebutuhan industri dan militer Jepang, terutama untuk armada angkatan laut mereka.
Dampak Jangka Panjang Eksploitasi Alam
Meskipun setelah pendudukan Jepang ada beberapa upaya reboisasi, dampak kerusakan alam yang terjadi sangat besar dan terus terasa hingga kini. Kerusakan yang diakibatkan oleh pembukaan hutan yang tidak terkendali masih berdampak pada keseimbangan ekosistem, perubahan iklim, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Baca juga: Pengcab KKI Bandar Lampung Pimpinan Mahathir Muhammad Dikukuhkan
Pentingnya Hari Konservasi Alam Sedunia
Hari Konservasi Alam Sedunia, yang diperingati pada 28 Juli, mengingatkan kita akan pentingnya melindungi alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia memiliki jejak panjang dalam eksploitasi alam, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang, yang telah menimbulkan dampak ekologis yang besar.
Peringatan ini bukan hanya sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga sebagai ajakan bagi semua pihak untuk terus berperan aktif dalam konservasi dan menjaga bumi untuk generasi mendatang.
Penulis: Fiska Anggraini